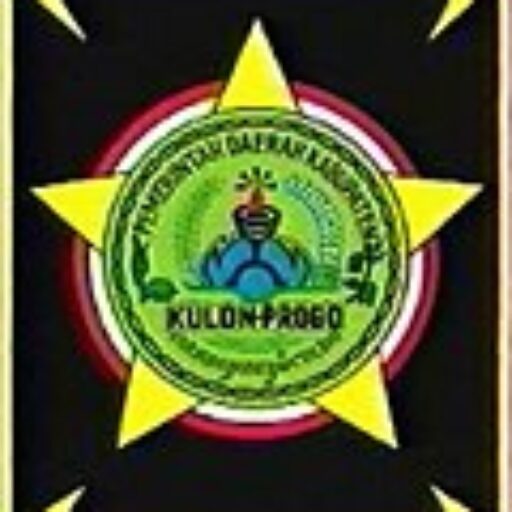
Desa Berkarya, Warga Berdaya
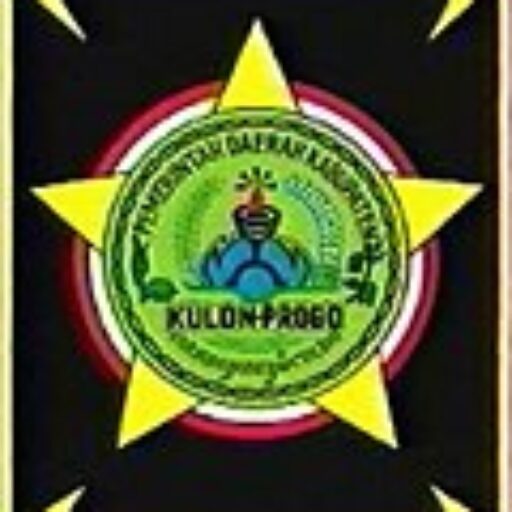
Desa Berkarya, Warga Berdaya
Potensi sdm: seni budaya lokal
Desa Hargomulyo, dikenal sebagai mandiri yang di dalamnya menyajikan banyak kesenian seperti halnya: Kethoprak, Selawat (Sholawat Nabi), Tari Angguk, dan Reog. Hal ini membuat banyak pihak dari luar desa tertarik untuk mengadakan kerjasama antarkelompok kesenian, khususnya di bulan Sura. Beberapa di antaranya ada yang menjadi kesenian unggulan di Desa Hargomulyo bahkan menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Kulon Progo yakni, Tari angguk. Berikut terdapat beberapa penjelasan mengenai kesenian Desa Hargomulyo, tepatnya di Pedukuhan Tangkisan III:
Kesenian kethoprak di Tangkisan III memiliki sejarah panjang sebelum berkembang seperti saat ini. Sebelumnya, masyarakat lebih dulu mengenal kesenian wayang wong. Selain kesenian wayang wong, terdapat pula kesenian tari gambyong yang ada sebelum kesenian karawitan hadir seperti yang dikenal sekarang. Saat ini, kegiatan kethoprak aktif dilatih oleh Pak Rubi yang merupakan seorang dalang lulusan ISI Yogyakarta bersama dengan Pak Parno, pemilik Paguyuban Kethoprak Sedyo Rukun. Selain menjadi pelatih, Pak Rubi juga bertugas sebagai sutradara, meskipun dalam kegiatannya, penyutradaraan juga dijalankan secara bergilir antaranggota untuk menciptakan lakon yang lebih bervariasi serta berkualitas. Hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga keaslian naskah yang sudah dibuat oleh para pelaku seni kethoprak. Naskah pementasan dibuat sendiri oleh kelompok tersebut dengan mengangkat tema-tema lokal seperti Babad Tangkisan dan cerita nenek moyang.
Dalam Paguyuban Kethoprak Sedyo Rukun, dilaksanakan latihan rutin setiap malam Kamis dan malam Minggu. Namun, menjelang pementasan, intensitas latihan akan ditambah demi hasil yang lebih maksimal. Biasanya, kelompok ini juga tampil dalam acara resmi pemerintah, seperti yang direncanakan pada bulan Juli atau Agustus di Wates, meski untuk tanggalnya masih menunggu kepastian. Naskah yang ditampilkan biasanya mengambil dari cerita lokal yang terdapat di wilayah masing-masing. Sementara lakon yang mengikuti pementasan, menggunakan tokoh yang sudah mahir dalam perannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Sunardi, tidak ditemukan peran ganda dalam sebuah pementasan kethoprak, hanya saja terdapat salah satu tokohnya mengalami transisi dari masa muda ke masa tua. Untuk ending yang disuguhkan biasanya menceritakan mengenai kejahatan yang kalah karena melawan kebaikan.
Menurut Pak Parno, pemilik Paguyuban Kethoprak Sedyo Rukun, dalam satu pementasan jumlah wiyaga atau yang biasa dikenal sebagai penabuh gamelan berkisar antara 16-20 orang. Terdiri dari pemeran perempuan yang beranggotakan sekitar 5-6 orang, sedangkan jumlah pemeran laki-laki lebih banyak. Tembang yang digunakan terdiri dari tembang macapat seperti Asmarandana untuk jejeran atau awalan, tembang dolanan yang digunakan saat dagelan, Asmarandana yang dipakai untuk adegan romansa dengan gending Sinom serta tembang Pucung. Bahasa yang digunakan dalam naskah pementasan memadukan bahasa ngoko dan krama.
Kesenian kethoprak yang diiringi dengan wiyaga juga dilengkapi gamelan laras pelog dan slendro, serta sinden yang berasal dari keluarga Bu Ipung. Durasi pementasan kethoprak yang disajikan biasanya cukup panjang, yakni 3-4 jam, dimulai sekitar pukul 21.30 hingga 02.00 dini hari.
Adapun struktur kepengurusan Kethoprak Sedyo Rukun seperti berikut:
- Ketua: Pak Tarji
- Wakil Ketua: Pak Sunardi
- Pelatih: Pak Parno, Pak Rubi, Bu Sunusi, dan Pak Supandi

Kesenian selawat (Sholawat Nabi) yang terdapat di Tangkisan III sudah ada sejak zaman dahulu. Jenis selawat yang digunakan adalah selawat Jawa. Dalam selawat Jawa dibagi menjadi dua yaitu: Selawat Mondreng atau Mantra yang dalam pembacaannya banyak menggunakan bahasa Jawa. Selain Selawat Mondreng terdapat juga Selawat Maulud yang banyak menggunakan bahasa Arab (campuran bahasa Jawa dan bahasa Arab).
Tangkisan III memiliki 4 kelompok kesenian selawat, antara lain: At-Tur Jati, Al-Badar, Jami’i Salam, dan Mangun Karya. Kelompok tersebut terdapat di RT 78 dan 79, RW 23 serta RT 88 dan 89, RW 25. Berbeda halnya dengan kesenian selawat yang terdapat di daerah Tangkisan II, kesenian selawat di Tangkisan III hanya beranggotakan jemaah laki-laki. Sementara untuk jemaah perempuan mengikuti kegiatan barzanji atau biasa disebut dengan berjanjen. Jumlah jemaah yang mengikuti kegiatan ini beranggotakan 15-30 orang.

Kegiatan yang diketuai oleh Pak Marsudin biasanya dimulai pada pukul 21.00-selesai, berkisar antara jam 00.00-01.30 pada malam Minggu Pon yang diadakan di masjid, Musala Karangjati serta musala milik Mbah Marno yang terdapat di RT 78. Sedangkan bagi jemaah perempuan yang mengikuti barzanji, biasanya diadakan pada malam Minggu Pahing pukul 20.00-22.30 di musala. Kitab yang digunakan untuk membaca selawat sama halnya dengan yang digunakan untuk barzanji, yaitu kitab Syaroful Anam.  Kesenian yang dilakukan setiap 35 hari sekali, tidak ada yang berganti dalam bacaannya, namun terdapat variasi pada iringannya. Untuk Iringan yang digunakan dalam musik selawat Jawa ada 5 buah antara lain: Kenting dan Kentung (terbang yang berukuran kecil), Kempul (terbang yang berukuran sedang), Gong (terbang yang berukuran besar), serta Kendhang.
Kesenian yang dilakukan setiap 35 hari sekali, tidak ada yang berganti dalam bacaannya, namun terdapat variasi pada iringannya. Untuk Iringan yang digunakan dalam musik selawat Jawa ada 5 buah antara lain: Kenting dan Kentung (terbang yang berukuran kecil), Kempul (terbang yang berukuran sedang), Gong (terbang yang berukuran besar), serta Kendhang.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Kaum Rois, beliau mengatakan bahwasannya terdapat pelatihan selawat yang diadakan di tempat tinggalnya disebut dengan istilah “Mblajarke Sholawat”, yang bertujuan untuk regenerasi kesenian selawat. Selain itu, pada bulan Ruwah, Pasa, dan Syawal tidak diadakan kegiatan tersebut karena diadakan tahlilan di masjid pada bulan Ruwah dan difokuskan untuk beribadah selama bulan Ramadan atau bulan Pasa. Selawat diadakan kembali pada bulan Zulkaidah atau bulan Dzulqa’dah. Menurut Mbah Kaum Rois, salah satu hal yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan selawat adalah mendapat undangan dari luar Padukuhan Tangkisan III untuk mengisi kegiatan selawat karena dirasa indah.

Kulon Progo yang menjadi salah satu pelopor berdirinya kesenian Tari Angguk sudah ada sejak tahun 1979 untuk kesenian Angguk Putra dan diikuti dengan kesenian Angguk Putri pada tahun 1990. Tarian tersebut pada awalnya hanya berkembang di Padukuhan Pripih. Seiring berkembangnya zaman, tarian Angguk ini menduduki posisi sebagai salah satu ciri khas Kabupaten Kulon Progo.
Padukuhan Tangkisan III, menjadi salah satu padukuhan yang turut melestarikan kesenian tersebut. Melihat antusiasme yang tinggi terhadap seni tari, membuat salah satu pelaku seni yang bertempat tinggal di sana, Bu Ipung, tergerak untuk membuka sanggar sebagai fasilitas masyarakat mulai tahun 2012 hingga saat ini. Terdapat beberapa tarian yang diajarkan di sanggar tersebut antara lain: tari Angguk, tari kreasi, tari garapan, dan tari Klasik yang berfokus pada tari Nawung Sekar dan tari Golek Ayun-Ayun.

Siswa yang mengikuti sanggar tersebut dibagi menjadi beberapa tingkatan mengikuti usia mereka. Biasanya tari Angguk dipentaskan untuk semua umur, termasuk kelompok ibu-ibu. Sementara tari kreasi dan tari garapan biasanya diikuti oleh anak-anak SD, sedangkan untuk tari klasik kebanyakan diikuti oleh siswa SMP atau yang usianya sudah lebih di atas mereka.
Ibu Ipung, selaku pemilik Sanggar Seni Perwita biasanya mengadakan uji kompetensi kepada para siswanya setiap 6 bulan sekali atau satu semester untuk menilai kemampuan mereka. Nantinya, jika sudah lulus di salah satu tingkatan maka akan naik ke tingkatan berikutnya. Durasi yang disuguhkan dalam setiap tarinya berbeda-beda. Tari Nawung Sekar, atau tari klasik dasar berdurasi kurang lebih 5 menit. Sedangkan Tari Golek Ayun-Ayun berdurasi 9 menit, namun hanya berfokus pada bagian intinya, atau biasa disebut dengan maju gendhing. Untuk tari Angguk sendiri berdurasi 5-9 menit.
Tari yang menjadi ciri khas Kulon Progo ini sering dipilih untuk pembuka acara pementasan dan juga penyambutan tamu dari luar daerah. Biasanya diadakan di Sendang Pengilon, tepatnya di Padukuhan Banjaran.

Dalam sejarahnya, kesenian reog berasal dari Keraton Yogyakarta yang kemudian terpecah menjadi empat bagian, yaitu wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Penamaan kesenian tersebut di masing-masing wilayahnya tetap menggunakan istilah “Reog”, seperti di daerah Bantul, Sleman, Gunungkidul (Wonogiri), dan Kulon Progo. Kesenian Reog di Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 7 kelompok. Kesenian ini berkembang dari bentuk penyamaran prajurit Mataram dengan nama sandi “Lombok Abang” yang kemudian menyebar hingga Padukuhan Tapen. Untuk alat-alat yang digunakan membawa dari keraton.

Cerita yang disajikan di setiap wilayahnya mengangkat cerita yang bervariatif. Kesenian reog di Bantul, khususnya daerah Brosot menceritakan kisah Ramayana. Sementara di Sleman masih mengangkat cerita yang sama, Ramayana (Sugriwa dan Subali). Lain halnya dengan Kulon Progo yang mengangkat cerita Panji Asmara Bangun.
Kesenian yang berasal dari keraton Yogyakarta ini menggunakan iringan musik klasik. Sedangkan lagu yang ditembangkan menggunakan pakem reog. Dari tembang tersebut juga diciptakan tari kreasi. Berbeda dengan Reog Ponorogo yang terdapat di Jawa Timur, kesenian reog yang ada di Kulon Progo khususnya Tangkisan III, tidak terdapat unsur kesurupan dan tidak menggunakan barongan dan juga merak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kesenian reog di Tangkisan III, Pak Sutarman mengatakan dilakukan latihan rutin pada hari Sabtu atau Minggu. Penampilan terakhir digelar di Sendang Pengilon dan Balai Desa. Saat pementasan, ada 32 orang terlibat: 12 wiyaga (penabuh) dan 22 penari gabungan laki-laki dan perempuan. Reog di Yogyakarta menjadi bentuk pelestarian budaya yang tetap hidup dan kontekstual hingga kini.